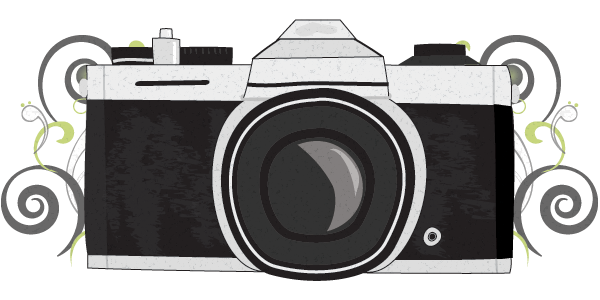Minggu (30/6) secara mendadak saya memutuskan untuk mengajak teman-teman saya menonton Ariah. Tontonan tersebut adalah teater. Dengan desain sedemikian rupa di lapangan Monas, menjadi sebuah panggung megah. Salah satu yang menarik minat para pengunjung adalah, biaya masuk ke teater ini amat sangat terjangkau. Untuk kelas festival rakyat dijual seharga Rp 2.000 dan bahkan di hari terakhir pertunjukan ini digratiskan.
Saya penasaran dengan beberapa celotehan di social media yang menceritakan betapa meriahya Ariah ini. Saya pikir, kapan lagi bisa mendapatkan hiburan berkelas dengan harga murah? Maka saya segera menghubungi teman-teman saya untuk menonton. Tapi kami terlambat datang.
Acara seharusnya dimulai pukul 19.00 sesuai jadwal yang terpasang. Namun kami sendiri baru berkumpul sekitar 19.15. Kami berempat. Ada saya, Ikyu dan pacarnya, Tika serta Hansen. Usai berkumpul, kami memutuskan untuk mencari tahu bagaimana cara masuknya. Ternyata yang tiket Rp 2.000 hanya dapat dibeli di kelurahan. Sementara banyak calo yang berkeliaran menjual tiket semau pemerintah menaikkan harga BBM. Mereka jual dengan varian Rp 15.000 hingga Rp 25.000. Luar biasa.
Sementara itu saya juga sempat dengar isu mengenai pintu masuk gratis. Tapi ternyata sudah dibuka ketika pukul 18.00 dan saat kami sampai, sudah tertutup. Setelah mengelilingi Monas satu putaran dari pintu masuk Bank Indonesia-pintu Gambir-pintu masuk BI lagi-tengah Monas, diskusi dengan seksama, dan berpikir keras, akhirnya kami memutuskan untuk tetap menonton melalui layar lebar yang disediakan di luar area teater.
Saat berjalan kembali ke tengah Monas, saya dan Hansen mengincar salah satu jajanan khas yang sering ada di Monas: Kerak Telor. Tapi, rekan saya yang satu itu entah sudah tidak bisa menahan lapar lagi atau memang belum pernah makan atau memang aneh, dia berpesan ke penjualnya agar kerak telor pesanannya tidak pedas. Ya, saya tau sih dia tidak bisa makan pedas. Tapi ya…
Nah, keseruan yang sesungguhnya muncul ketika kami berempat mencari posisi yang nyaman untuk menonton layar tancap tersebut. Sempat duduk di belakang, tapi yang depan tetap berdiri tanpa peduli. Akhirnya kami pindah ke depan. Saya duduk di samping ibu-ibu paruh baya. Dia sempat sedikit komentar ketika teman saya, Ikyu mengeluh tetap sulit menonton dari sudut ini. “Ya di sini memang susah mas nontonnya. Tapi nikmatin saja,”
Karena layar tancap, jadi kondisi yang menonton pun apa adanya. Ada yang menyewa tikar untuk duduk. Ada yang niat membawa semacam kasur tipis. Ada yang duduk di dekat tempat menonton layar, tapi asik bercengkrama dengan pasangan di sampingnya (kalau ada). Kalau tidak ada? Tidur. Gaya menontonnya pun beragam. Ada yang fokusnya setengah menonton (atau mungkin seperempat), sisanya melihat handphone. Ada yang sambil kerokan. Ada yang tidur di paha pasangannya. Tapi ya mungkin seperti ini kira-kira gambaran masyarakat Jakarta yang beragam.
Sebetulnya kalau mau serius menonton juga sulit. Kondisinya amat sangat ramai. Suara melalui speaker yang dipasang panitia sebenarnya hanya untuk melayani penonton yang di dalam saja. Jadi yang di bagian luar cuma dapat sisanya. Sisa-sisa suara itu masih harus diperebutkan dengan banyaknya pedagang yang berlalu-lalang, suara anak kecil menangis, atau suara orang-orang yang sedang bercendi gkrama. Maka saya tidak tahu, kenapa ibu-ibu di sebelah saya tadi sampai serius sekali menontonnya. Bahkan sesekali tertawa. Padahal tidak kedengaran apa-apa.
Tempat saya menonton juga sempat rusuh. Ada seorang bapak-bapak sedang menyewakan tikar miliknya. Dengan lantang ia berteriak “Lima ribu satu! Empat, dua puluh!”. Tidak lama, gerombolan ibu-ibu di belakang saya celoteh “Lah, itu mah sama aja pak!”. Ibu-ibu tersebut tampaknya ingin menyewa tikar dari si Bapak. Tikarnya sudah diambil, dan diduduki. Namun ketika hendak membayar, Ibu-Ibu ini menawar. “Tiga ribu aja lah pak!”.
Entah karena si Bapak ini belum makan malam, atau mungkin bingung untuk membayar tagihan yang jatuh esok hari, dengan paksa ia merebut tikar tersebut. Lalu ia berteriak. “UDAH SINI KALAU ENGGAK MAU YAUDAH. UDAH DIBILANG LIMA RIBU JUGA. ORANG UDAH TERIAK-TERIAK SAMPE SUARA SEREK GINI,”
Sejenak saya merasa seperti ada di teater dalam teater.
Suasana sempat tenang sampai beberapa menit kemudian ada penjual es krim lewat. Kalau cuma lewat sih mungkin masih mending ya. Tapi ini: lewat di depan kita pakai sepeda dengan lampu menyala di boks belakang serta musik dengan volume paling kencang. Ternyata si pedagang bukan cuma lewat. Tiba-tiba dia parkir. Di depan. Dan dia duduk manis ikut nonton.
Saya sih bukan mau melarang dia menonton dan fokus jualan saja. Tapi masalahnya sinar lampunya silau karena parkir benar-benar di depan saya. Belum lagi theme song es krimnya yang kencang. Akhirnya mas-mas es krim tersebut pergi. Diusir sama bapak-bapak di depan saya.
Cerita teater dalam teater ini ditutup ketika ada sepasang ondel-ondel lewat. Lengkap dengan ember, mereka meminta para pengunjung yang saat itu sedang duduk-duduk. Anaknya bapak-bapak yang ngusir mas-mas tukang es krim tadi langsung menjerit takut ketika ia bangun dari rebahan. Ya, siapa yang tidak kaget, kalau anda noleh, tau-tau ada ondel-ondel nyengir bawa ember cat di depan muka.
Mungkin akan menjadi sebuah cerita yang panjang jika kami menonton teater Ariah sampai habis. Tapi karena sudah tidak ada yang menarik, kami memutuskan pulang. Entah apa yang membuat orang-orang tadi masih betah berjam-jam menonton dari luar.
Sisi dalam teater Ariah seperti menggambarkan sisi glamor Jakarta. Kemewahan, keistimewaan. Tapi itu sisi kulitnya. Sisi intinya justru berada di luar, yang menjadi realita keseharian kota tersebut.